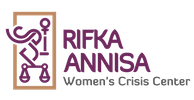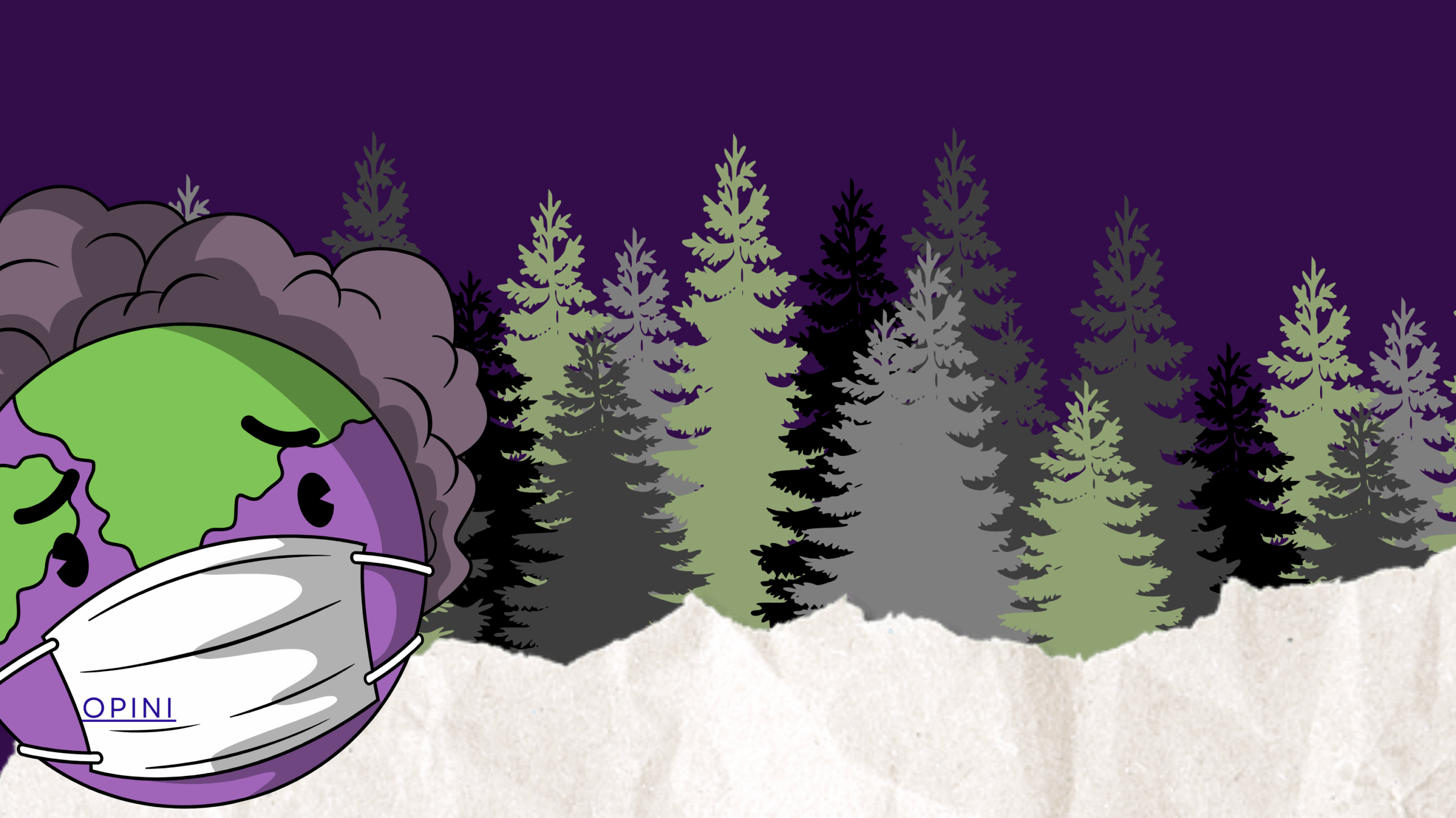Krisis Iklim dan Ancaman Kekerasan Berbasis Gender di Tanah Papua
“Hutan itu seperti supermarket bagi mama. Semua kebutuhan harian mereka ambil di sana. Ketika hutan dibabat, lalu dari mana mereka harus ambil makanan untuk kehidupan sehari-hari?!”
Begitulah kata Kak Leskie (bukan nama sebenarnya), seorang perempuan yang lahir dan besar di Merauke, Papua Selatan. Dengan semangat, ia menceritakan pengalamannya kepada penulis tentang krisis iklim yang dirasakan perempuan-perempuan adat di Papua.
Krisis iklim dan ancaman kekerasan kekerasan berbasis gender, tidak lepas dari kondisi perubahan yang disebabkan oleh gejala alamiah, seperti pola suhu, siklus matahari, dan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari tindakan manusia. Beberapa tahun belakangan, perubahan iklim semakin tidak terkontrol lantaran penggunaan energi fosil, deforestasi, dan eksploitasi sumber daya alam terus-menerus, hingga aktivitas manusia yang selalu meninggalkan jejak iklim. Pada akhirnya, narasi ‘krisis iklim’ hadir untuk mendesak pembuat kebijakan agar segera bertindak, sekaligus mendorong perhatian publik dalam aksi iklim global. Krisis ini mengakibatkan peningkatan suhu, mencairnya lapisan gletser, dan kenaikan permukaan air laut, serta meningkatkan intensitas bencana alam (banjir, longsor, dan kekeringan) yang bisa memicu gangguan climate anxiety (kecemasan iklim).
Krisis iklim juga mempengaruhi topografi wilayah Merauke yang datarannya relatif rendah dan berawa. Pada saat musim hujan, bencana banjir sering kali terjadi dan membuat air yang menggenang semakin lama surut. Begitu juga musim kemarau, kekeringan kerap membuat struktur tanah berubah menjadi keras, gersang dan pecah-pecah. Seorang peneliti Balai Besar Sumber Daya Lahan Pertanian, D. Djaenudin dalam penelitian berjudul Potensi Sumber Daya Lahan untuk Perluasan Areal Tanaman Pangan di Kabupaten Merauke yang dipublikasikan sejak tahun 2007, memaparkan bahwa dataran Merauke didominasi oleh tekstur tanah aluvial, yaitu jenis tanah yang terbentuk dari endapan aliran lumpur sungai. Dalam konteks tersebut, kebutuhan air bersih di Merauke menjadi sangat terbatas, karena saat hujan tiba, air akan bercampur lumpur sekaligus berubah warna menjadi merah-kecoklatan. Terlebih, kemarau panjang membuat sejumlah sumur tanah di Merauke mengalami kekeringan.
“Ketika musim hujan, air naik sampai dimana-mana banjir. Tapi ketika musim panas kering itu panjang, dan sumur-sumur, tanah, sawah itu pecah-pecah, gak ada yang bisa ditanami dan kami harus mencari air bersih walaupun ada PDAM, ada rawa biru, airnya [tetap] jadi kuning.”
Dalam kehidupan sehari-hari, perempuan memerlukan lebih banyak air untuk merawat, menjaga dan memelihara kesehatan reproduksi. Terlebih, perempuan memiliki organ reproduksi yang kompleks, setiap bulan ia mengalami menstruasi sehingga membutuhkan air untuk sanitasi dan konsumsi, begitupun saat hamil, melahirkan dan menyusui. Bahkan intensitas buang air kecil perempuan lebih sering dibandingkan laki-laki, maka air bersih menjadi kebutuhan pokok yang tidak bisa dihindari bagi perempuan. Selain itu, perempuan masih dibebankan pada urusan domestik, dalam keadaan apapun, ia akan selalu memikirkan anak, suami, dan keluarga. Ketika tidak ada air, maka perempuan tidak bisa memasak, minum, mencuci juga membersihkan organ reproduksi, yang mengharuskannya pergi untuk mencari sekalipun harus menempuh jarak jauh. Temuan WHO bersama UNICEF dalam “Progress on household drinking water, sanitation and hygiene 2000-2022: Special focus on gender”, 7 dari 10 perempuan dan anak perempuan di dunia masih memikul tanggung jawab mengambil air untuk kebutuhan rumah tangga, mereka harus menempuh perjalanan jauh sehingga kehilangan waktu untuk sekolah, bekerja, dan beristirahat. Sama halnya pada saat perjalanan, perempuan dan anak perempuan rentan mengalami risiko cedera fisik, pelecehan dan juga kekerasan.
Lebih dari itu, wilayah Merauke kini ditetapkan menjadi kawasan Food Estate yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Artinya, ada pembukaan lahan baru besar-besaran yang menambah kerusakan lingkungan dan memperparah ketimpangan, terutama masyarakat adat yang menempatkan alam sebagai penopang kehidupan. Sebelum kehadiran PSN, masyarakat adat sudah dihadapkan oleh gangguan investor dan kriminalisasi aparat keamanan. Mereka merebut hak ulayat demi memperoleh keuntungan melalui perusahaan perkebunan yang diprivatisasi. Dengan menggantikan hutan menjadi area tanam monokultur yang rentan terhadap hama, penyakit dan ketergantungan terhadap pupuk kimia. Situasi tersebut turut mempercepat kerusakan iklim global.
Kawasan hutan Papua yang luas mampu menyerap karbon dioksida (CO2) dan menghasilkan oksigen (O2) dalam jumlah besar, bahkan dianggap sebagai “paru-paru dunia”. Bagi masyarakat adat di Merauke, hutan sendiri bukan sekadar hamparan pepohonan, melainkan sebuah nilai dan identitas yang diwariskan leluhur secara turun-temurun. Hubungan keduanya tergambar seperti sosok mama (ibu) yang harus dihormati, dilindungi dan dijaga hingga akhir hayat. Namun di satu sisi, nilai tersebut seakan berbanding terbalik ketika perempuan-perempuan di sana terhambat secara struktural dan kultural.
“Kenapa mama-mama perempuan ini yang paling ribut? Karena hutan itu kan dusun. Perempuan tuh mikir dari bangun pagi, [harus ambil] ubi atau sagu atau apapun yang bisa di makan anak-anak sama suami, itu tempatnya semua di dusun. Kalau semua dibangun seperti itu [PSN], di mana lagi mereka mencari. Satu hutan hilang, dua dusun hilang. Kita harus ingat bahwa secara adat orang Papua itu punya wilayah adat masing-masing. Ketika wilayah adatmu sudah dibuka untuk PSN dan ko tidak punya lagi wilayah adat, ko tidak bisa mencari makan seenaknya ke wilayah adat orang lain, kehilangan wilayahnya sa tidak ada, menumpang pun belum tentu dikasih.”
“Karena bujukan investor untuk pelepasan tanah, itu kan bukan milik orang satu doang [tapi] ke marga, jadi satu udah kesana tanda tangan pelepasan, yang lain gak tau, atau kepala kampung yang bujuk kesana, adat gak diajak ngomong dulu atau sebaliknya. Timbul konflik! Kalau ada konflik seperti itu, ya laki-laki jaga jarak, tidak mau terlibat, [mereka] pergi dengan kelompoknya. Tapi perempuan? ya harus tetap disitu. bagaimana anak-anaknya, rumahnya, jadi tetap disitu dengan segala tekanan yang ada.
Selama bertahun-tahun Kak Leskie mengamati kalau “membiarkan perut laki-laki kenyang, sama dengan menyelamatkan perempuan dari kekerasan”. Melekatnya budaya patriarki di tanah Papua, menempatkan perempuan pada posisi subordinasi, dan membatasi perempuan dalam mengakses sumber daya dan tanah. Sedang, disaat yang sama tanggung jawab atas keberlangsungan sumber daya pangan masih dibebankan kepada perempuan. Seperti yang diungkapkan Kak Leskie, pangkur sagu merupakan pekerjaan utama perempuan adat di Merauke. Mulai dari menebang, membersihkan, memarut, hingga memeras airnya yang dilakukan oleh perempuan sendiri, tak jarang mereka harus menginap di hutan hanya untuk menunggu endapan sagu yang terpisah dari air. Karena sagu merupakan makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari. Di saat perempuan tidak bisa menyajikan makanan karena hutan sudah hilang. Ancaman kekerasan seolah membayangi kehidupan mereka, meskipun kekerasan bisa terjadi dalam bentuk lain, tetapi lagi-lagi, perempuan adalah pihak pertama yang menjadi korban.
Rusaknya hutan berarti hilangnya separuh kehidupan perempuan. Di Merauke, perempuan tidak memiliki hak untuk mengikuti proses musyawarah adat, sementara keputusan sepenuhnya ditentukan oleh laki-laki. Ketika hutan dirampas, dirusak, dan dijual, pendekatan yang dilakukan cenderung maskulin (perang, kekerasan, bahkan pembunuhan). Dinamika seperti itu menambah konflik baru, perempuan dilemahkan, disingkirkan atas apa yang ia rawat selama ini dan hak-hak dasarnya terabaikan. Maka, peminggiran terhadap pengalaman perempuan dengan alam, pelemahan peran perempuan dalam pengambilan keputusan, menjauhkan perempuan dari sumber pangan, adalah bentuk penindasan, krisis iklim dan ancaman kekerasan berbasis gender sesungguhnya.
“Kalau suami bisa alasan apa saja. Kalau pun dia pergi berburu, belum tentu dia pergi berburu. Dia melarikan diri, kemana pun. Balik-balik juga ga bawa apa-apa. Tapi kalau perempuan, ya sulit. Dan kalau laki-laki pergi, ya pergi saja, tapi kalau mama nggak pulang [sampai] sore pasti sudah [ribut]”.
Antara krisis iklim dan kekerasan terhadap perempuan, keduanya merupakan persoalan sistemik dan struktural. Saat ini, banyak negara maju berlomba-lomba melakukan transisi energi yang berdampak negatif bagi negara-negara berkembang. Misalnya, Pembangkit Tenaga Listrik Panas Bumi (PLTPB) atau geothermal yang terletak di Padarincang, Kabupaten Serang, Banten yang masih dalam tahap eksplorasi, masyarakat setempat sudah merasakan dampak longsor dan banjir saat musim hujan, akibat lahan dan galian yang dibiarkan tanpa adanya upaya pemulihan lingkungan.
Baca Juga :Pemetaan Dampak Krisis Iklim terhadap Perempuan
Hal sama juga menunjukan ketimpangan relasi, di mana pola konsumsi dan produksi negara-negara maju wilayah Utara (Amerika Serikat, Inggris, Kanada hingga Italia), justru menyumbang emisi gas rumah kaca lebih besar yang berimbas pada kerusakan lingkungan negara berkembang di wilayah Selatan (Afrika, Asia dan Oceania), dengan memanfaatkan sumber daya alam, monopoli perdagangan karbon hingga pasar tenaga kerja upah rendah. Terlebih, negara di wilayah Selatan masih bergantung pada pertanian tradisional yang sensitif terhadap perubahan iklim, dan belum memiliki kapasitas adaptasi dan mitigasi krisis iklim dibandingkan negara-negara bagian Utara.
Sementara itu, konsep green economy merupakan cerminan dari praktik neocolonialism yang melahirkan eksploitasi baru (green neocolonialism) demi memenuhi kepentingan elite dan oligarki. Di Indonesia, praktik seperti itu terbentuk melalui mega proyek yang bersifat ekstraktif, seperti pertambangan, emas, batubara, dan nikel. Di mana aktor seperti negara dan korporasi dapat melanggengkan ketimpangan iklim yang dijalankan melalui sistem ekonomi-politik yang saling berkelindan dengan kapitalisme, kolonialisme, dan militerisme yang dibalut patriarki.
Perjuangan melawan krisis iklim dan ancaman kekerasan terhadap perempuan, tsebenarnya perjuangan melawan sistem yang eksploitatif dan tidak adil terhadap alam dan perempuan. Setiap individu juga dihadapkan pada situasi berlapis (multiple situation) yang tidak hanya ada ketimpangan relasi kuasa, tetapi juga ketimpangan berlapis dengan komunitas lokal maupun entitas global yang industrialis dan bergantung pada pasar. Relasi yang kuat seperti itu akan menyebabkan ketimpangan yang berlapis-lapis, di keluarga, ekonomi, budaya, gender, juga politik dan spiritual. Maka, transformasi keadilan iklim tidak cukup dengan melakukan konservasi maupun transisi energi, karena masih mengesampingkan praktik dan nilai-nilai tradisi lokal. Sedangkan penguatan pengetahuan lokal adalah basis utama dalam menangani krisis iklim. Masyarakat adat di Papua Selatan memiliki cara tersendiri dalam merawat dan menjaga lingkungan dari kerusakan, salah satunya melalui tradisi Sasi. Sasi adalah sebuah tradisi pengaturan wilayah untuk menjaga dusun (hutan), dengan cara mengunci wilayah tertentu dan tidak boleh dieksplorasi selama beberapa tahun.
“Nanti dia rasa sudah udah habis, dia kunci, dia buka yang di tengah misalnya, itu yang dimasukin, yang lain gak boleh diambil. Di Sasi itu ga boleh masuk, jadi ketika dia buka itu yang tadi dia ambil, sekian tahun lalu dia sasi, ketika dia buka itu kan sudah kembali semua kehidupannya. Keanekaragaman hayati kembali, yang tadi dia masuk itu udah ngambil sagu disitu, sekian lama dia pakai, dalam beberapa tahun dia ambil disitu aja, mungkin sagu yang besar-besar sudah gak ada tinggal sagu yang anakan-anakan gitu kan, itu kan tumbuh besar lagi. Kalau di situ dirasanya sudah, itu ditutup. Kunci lagi di Sasi. Pindah ke yang lain. Jadi, mereka punya aturan menjaga itu dengan Sasi”.
Sebagai tambahan, Kak Leskie bersama komunitasnya telah mendorong kedaulatan pangan bagi masyarakat adat yang dimulai dari halaman rumah, supaya mereka tidak perlu lagi pergi jauh untuk mencari sumber makanan. Mengakui kerja-kerja perawatan juga dapat mengatasi ketimpangan iklim. Caranya tidak membebankan seluruh pekerjaan kepada salah satu pihak, melainkan sebagai bagian dari tanggung jawab bersama baik laki-laki maupun perempuan, termasuk dalam menjaga alam dan lingkungan.
Pengetahuan dan pengalaman perempuan menjadi kekuatan dalam mengatasi krisis iklim dan ancaman kekerasan berbasis gender, terutama mereka di akar rumput. Begitu juga perlu ada ruang kepemimpinan perempuan untuk menyusun kembali kebijakan yang berspektif terhadap keadilan iklim dan keadilan gender untuk mengakhiri ketimpangan dan melawan krisis iklim. Demikian, mengedepankan transisi yang berkeadilan bagi alam semesta dan manusia adalah aspek fundamental yang harus dipenuhi untuk mengatasi krisis iklim berkelanjutan!
Referensi
- Djaenudin, D. (2007). Potensi Sumber Daya Lahan untuk Perluasan Areal Tanaman Pangan di Kabupaten Merauke. Puslitbang Tanaman Pangan.
- Leskie, komunikasi personal, Juni 20, 2025.
- Hasyim, I. (2024, Oktober 17). Masyarakat Adat Merauke Tolak PSN Food Estate: Proyek Berlangsung Brutal. Tempo.co. https://www.tempo.co/lingkungan/masyarakat-adat-merauke-tolak-psn-food-estate-proyek-berlangsung-brutal-405399
- Raisa, A. (2025, 30 Juni). Tiap Beko Datang, Kami Adang: Perempuan Padarincang Menolak Proyek Geothermal Banten. Project Multatuli. https://projectmultatuli.org/tiap-beko-datang-kami-adang-perempuan-padarincang-melawan-proyek-geothermal-banten/
- WHO-UNICEF. (2023, 6 Juli). Women and girls bear brunt of water and sanitation crisis – new UNICEF-WHO report. WHO. https://www.who.int/news/item/06-07-2023-women-and-girls-bear-brunt-of-water-and-sanitation-crisis—new-unicef-who-report
Tia Mega Utami saat ini aktif menjadi volunteer di Rifka Annisa WCC dan mahasiswa aktif Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik
Editor : Firda Ainun Ula