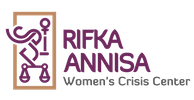Ketika Hukum Memerangkap Korban KDRT: Dilema Syarat Cerai Pisah Rumah 6 Bulan
Bayangkan seorang istri yang selama bertahun-tahun hidup dalam ketakutan. Suaminya kerap menghina, mengontrol, dan memukulnya. Suatu hari, ia memberanikan diri pergi—meninggalkan rumah untuk menyelamatkan diri. Namun, ketika ia mengajukan gugatan cerai, hukum berkata: “Tunggu dulu, Anda belum cukup lama berpisah rumah. Enam bulan, minimal.” Di sinilah dilema itu bermula. Peraturan yang seharusnya melindungi, justru berpotensi menjerat korban dalam situasi yang semakin berbahaya.
Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. SEMA ini bertujuan untuk menjaga keseragaman putusan pengadilan. Tetapi pengalaman pendampingan Rifka Annisa pada 2024 menemukan, aturan ini justru menghadirkan tantangan baru bagi korban KDRT yang ingin mengajukan gugatan cerai.
Di Indonesia, perceraian didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksana dari UU No. 1 Tahun 1974 yang diperbaharui dengan UU Nomor 16 Tahun 2019. Adapun pasal 19 dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tersebut menyebutkan, perceraian hanya dapat diajukan jika memenuhi salah satu atau lebih alasan berikut:
- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah.
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau lebih setelah perkawinan berlangsung.
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- Salah satu pihak mengalami cacat badan atau penyakit yang menyebabkan ketidakmampuan menjalankan kewajiban sebagai suami/istri.
- Antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa harapan hidup rukun kembali.
Dalam lima tahun terakhir, Rifka Annisa mencatat 477 kasus Kekerasan Terhadap Istri (KTI) dari total 1.158 kasus kekerasan berbasis gender yang didampingi. Tahun 2020 terdapat 150 kasus, tahun 2021 terdapat 109 kasus, tahun 2022 terdapat 76 kasus, dan tahun 2023 terdapat 68 kasus, dan tahun 2024 terdapat 74 kasus. Angka ini terlihat menurun setiap tahunnya. Realitasnya, kasus kekerasan terhadap istri tetap menjadi yang tertinggi. Ini dibandingkan dengan bentuk kekerasan lainnya, seperti pelecehan seksual, pemerkosaan, dan kekerasan dalam pacaran. Pengalaman pendampingan Rifka Annisa pada kasus KDRT menemukan, alasan perceraian yang paling sering diajukan adalah perselisihan yang terus-menerus dan tidak ada harapan rujuk.
Baca juga: Kasus Berproses Hukum Tahun 2024 Meningkat
Korban KDRT Terdesak Pilihan: Bertahan dalam Bahaya atau Menunggu Legalitas
Adapun UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) sebagai peraturan yang digunakan untuk penyelesaian kasus sejak dua dekade lalu masih menghadapi hambatan serius. Salah satunya adalah cara aparat penegak hukum memandang korban. Perempuan yang mengalami KDRT kerap distigmatisasi sebagai pemicu kekerasan, tidak konsisten dalam melapor, atau dianggap hanya bereaksi secara emosional sesaat. Akibatnya, banyak korban yang mengurungkan niat untuk melanjutkan proses hukum.
Pemberlakuan SEMA No. 3 Tahun 2023 menambah daftar hambatannya. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa gugatan perceraian dengan alasan perselisihan terus-menerus hanya dapat dikabulkan jika pasangan telah berpisah rumah selama minimal enam bulan. Kecuali, terdapat bukti hukum adanya KDRT:
“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.”
Bagi korban KDRT, meninggalkan rumah sudah bukan perkara mudah. Aturan yang muncul justru makin menyulitkan korban yang ingin segera keluar dari lingkaran kekerasan.
Dalam pengalaman pendampingan korban KDRT, setidaknya Rifka Annisa mencatat enam alasan mengapa aturan pisah rumah selama enam bulan ini menjadi penghambat bagi perempuan yang ingin bercerai sebagai berikut:
- Korban terpaksa memilih diam. Ketika suaminya mulai mencaci maki atau mengancam, korban cenderung tidak merespons karena takut situasi semakin memburuk. Akhirnya, mereka memilih menghindar dengan pergi dari rumah, meskipun ini belum memenuhi batas waktu enam bulan yang disyaratkan.
- Tekanan untuk kembali. Ketika korban sudah keluar rumah untuk menghindari suami dan akan mengajukan cerai ketika posisi korban sudah tidak serumah dengan suami, keputusan bisa berubah seketika. Ini karena suami bersama keluarga datang menjemput dengan bujukan dan janji perbaikan. Jika korban kembali meski durasi pisah telah mencapai 6 bulan, maka hitungan pisah rumah dianggap gugur.
- Kesulitan mendapatkan bukti KDRT. Tidak semua korban bisa segera melakukan pemeriksaan medis dengan mudah setelah mengalami kekerasan karena biasanya pelaku akan mengawasi. Sering kali, bekas luka fisik telah hilang saat korban akhirnya berani mencari bantuan.
- Penelantaran ekonomi yang sulit dibuktikan. Istri yang tidak mendapatkan nafkah dari suami secara materi setiap bulan dapat dikatakan bentuk penelantaran sebagaimana diatur dalam UU PKDRT. Namun, unsur penelantaran dapat terpenuhi jika terjadi selama kurang lebih 2 (dua) tahun, sedangkan ketika suami memberikan nafkah dengan nilai seberapapun baik dalam bentuk harian, mingguan, maupun bulanan, dapat didefinisikan sebagai bentuk nafkah. Maka, kondisi penelantaran yang beragam sulit digunakan sebagai bukti hukum.
- Beban psikologis korban. Banyak perempuan yang bertahan dalam rumah tangga penuh kekerasan karena alasan anak, tekanan sosial, atau bahkan merasa kasihan pada suami. Ketika mereka akhirnya berani pergi, aturan enam bulan justru menjadi penghalang baru.
- Dampak dari aturan ini tidak bisa dianggap sepele. Jika korban terpaksa menunggu selama enam bulan, ada risiko tinggi pelaku akan menemukannya dan melakukan tindakan kekerasan lebih ekstrem. Dalam beberapa kasus, bahkan bisa berujung pada pembunuhan. Selain itu, kondisi psikologis korban yang harus menunggu dalam ketidakpastian bisa memburuk. Misalnya dengan meningkatnya risiko depresi, melukai diri sendiri, hingga bunuh diri.
Menutup Celah Kekerasan dalam Sistem Hukum
Kehadiran SEMA No. 3 Tahun 2023 yang bermaksud memberikan kepastian hukum dalam konsistensi putusan pengadilan, khususnya terhadap kasus perkawinan, menjadi dilematis bagi perempuan korban KRDT. Meskipun SEMA tetap membuka ruang bahwa alasan perceraian dapat menggunakan adanya KDRT, tetapi membuktikan adanya KDRT tidak mudah. Baik karena tidak bisa segera melakukan pemeriksaan, maupun peristiwa KDRT yang tidak terjadi di ruang publik, sehingga tidak ada alat bukti yang mendukung terutama saksi. Pilihan korban untuk memulihkan kondisi psikologisnya dengan pergi dari kediaman bersama pun kerap kali tidak cukup mendapat dukungan dari keluarga, kerabat, maupun rekan korban.
Oleh karena itu, implementasi SEMA No. 3 Tahun 2023 memerlukan kecermatan siapa pun yang mengajukan maupun melakukan pendampingan-pendampingan terhadap permasalahan perkawinan khususnya upaya hukum dengan gugatan perceraian. Kecermatan merujuk pada memastikan alat bukti dan saksi mencukupi untuk memenuhi ketentuan dalam SEMA No. 3 Tahun 2023. Implementasi kebijakan ini perlu dievaluasi agar tidak menjadi bumerang bagi korban KDRT. Setidaknya, ada tiga hal yang harus dipertimbangkan:
- Merevisi ketentuan pisah rumah minimal enam bulan. Ukuran waktu ini tidak mencerminkan kompleksitas kekerasan dalam rumah tangga. Syarat peraturan akan lebih mengakomodasi korban jika minimal 6 (enam) bulan adalah peristiwa konflik yang terjadi secara terus-menerus baik pisah rumah maupun tidak pisah rumah.
- Mengakomodasi dinamika korban KDRT. Keputusan untuk meninggalkan rumah bukanlah hal yang mudah. Regulasi harus mempertimbangkan bahwa perempuan sering terpaksa kembali ke rumah pelaku akibat tekanan keluarga atau kondisi ekonomi.
- Meningkatkan akses terhadap bukti KDRT. Banyak korban tidak bisa segera melaporkan kekerasan yang mereka alami. Oleh karena itu, perlu mekanisme pembuktian yang lebih fleksibel, seperti kesaksian dari tenaga kesehatan, konselor, atau organisasi pendamping.
SEMA akan lebih maksimal diterapkan dan dipatuhi jika mampu mengakomodir berbagai situasi di lapangan. Serta, memahami dinamika permasalahan korban yang harus menempuh jalur hukum sebagai upaya terakhir (Ultimum Remedium). Persoalan rumah tangga bukanlah sesuatu yang langsung dibawa ke pengadilan tanpa upaya lain. Pada kenyataannya, pasangan yang mengajukan perceraian telah menempuh mediasi atau penyelesaian kekeluargaan sebelumnya. Bahkan, dalam posita (alasan mengajukan gugatan), harus termuat klausul bahwa mediasi telah dilakukan. Hakim pun wajib mengupayakan perdamaian sebelum putusan dijatuhkan.
Jika upaya mediasi dan penyelesaian kekeluargaan sudah ditempuh tetapi tetap gagal, tidak ada jaminan bahwa memaksa pasangan untuk rujuk akan menghasilkan rumah tangga yang harmonis. Justru, hal ini bisa semakin memperpanjang penderitaan korban. Oleh karena itu, kebijakan hukum harus berpihak pada perlindungan korban. Bukan menjadi penghalang bagi mereka yang ingin keluar dari lingkaran kekerasan.
Aturan pisah rumah enam bulan dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 menunjukkan regulasi hukum masih kurang sensitif terhadap realitas korban KDRT. Jika sistem hukum tetap mempertahankan syarat ini tanpa mempertimbangkan aspek keselamatan korban, maka kita telah gagal dalam memberikan perlindungan yang seharusnya menjadi hak mereka.
Sebagai masyarakat, kita perlu terus mengawal kebijakan ini. Evaluasi hukum harus dilakukan dengan perspektif yang lebih berpihak pada korban, bukan sekadar formalitas legal. Jika hukum masih belum mampu melihat dinamika kompleks yang dihadapi korban KDRT, maka keadilan akan selalu terasa jauh dari jangkauan mereka. Kini, pertanyaannya: apakah kita akan terus membiarkan hukum menjadi penjara bagi korban, atau kita akan mendorong perubahan agar hukum benar-benar menjadi alat perlindungan yang nyata?
Penulis: Arnita Ernauli Marbun
Editor: Syaima Sabine Fasawwa
***
Artikel ini merupakan bagian dari Wajah Kekerasan 2024, yaitu laporan refleksi pengalaman pendampingan kasus kekerasan berbasis gender Rifka Annisa Women’s Crisis Center.