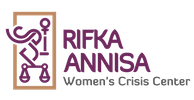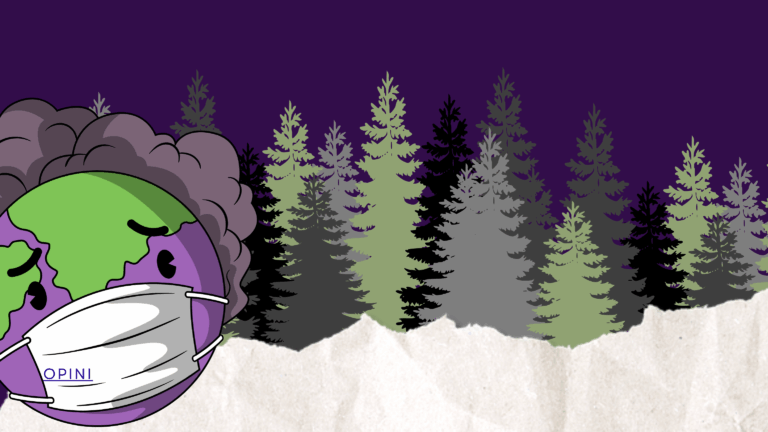Jurnalisme Berkeadilan untuk Korban Kekerasan Seksual
Kekerasan seksual adalah fenomena gunung es: banyak kasus yang terjadi, namun hanya sedikit yang muncul ke permukaan. Banyak korban memilih diam karena takut, malu, tak tahu harus lapor ke mana, atau juga tak percaya pada sistem yang ada. Dalam situasi ini, jurnalis memegang peran penting. Bukan hanya sebagai penyampai informasi, melainkan juga sebagai pemulih harapan, serta sebagai jembatan bagi suara yang nyaris tak terdengar. Dalam menjalankan peran ini, jurnalis perlu menempatkan kekerasan seksual bukan sebagai peristiwa kriminal saja. Kekerasan seksual merupakan cerminan relasi kuasa pelaku yang menimbulkan trauma berlapis bagi korban—tak hanya secara fisik, melainkan mental maupun kehidupan sosial. Karenanya, mengungkap dan memberitakan kasus kekerasan seksual tidak pernah mudah.
Dalam diskusi bertajuk “Mewujudkan Jurnalisme yang Peka Gender dan Inklusif” di Sekretariat Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta pada Sabtu (10/05/2025), Shinta Maharani—Ketua Bidang Gender, Anak dan Kelompok Marjinal AJI—menegaskan, liputan atas kasus seperti ini membutuhkan pendekatan yang penuh empati, sensitif, dan berperspektif korban. Maka, peliputan kasus kekerasan seksual menuntut lebih dari sekadar kemampuan teknis—ia memerlukan keberpihakan yang sadar, kepekaan yang terasah, empati yang tidak mengaburkan fakta, dan, tak kalah penting, kondisi jurnalis yang aman secara psikologis, sehingga tidak menimbulkan bias.
Hal utama yang perlu dipahami di sini adalah bahwa setiap korban membawa luka berbeda. Pengalaman kekerasan seksual menyentuh lapisan paling pribadi dari diri seseorang. Karena itu, pendekatan yang digunakan jurnalis harus menempatkan korban sebagai subjek yang dihargai, melebihi sebatas narasumber. Ini berarti, jurnalis perlu mendengarkan dengan penuh empati, menciptakan ruang aman, dan menulis dengan hati-hati. Bahkan sebelum wawancara dimulai, proses membangun kepercayaan harus dilakukan dengan sabar dan tulus. Sebab, kepercayaan tidak lahir dalam sehari.
Korban membutuhkan waktu untuk merasa aman dan nyaman dalam berbicara. Jurnalis perlu menghormati tempo korban. Tempat bertemu, waktu, termasuk medium komunikasi, harus menyesuaikan kenyamanan korban. Dalam konteks era digital, jurnalis juga perlu memastikan aspek keamanan dalam berkomunikasi dengan korban. Komunikasi antara jurnalis dan korban sebaiknya dilakukan melalui platform yang aman dan tidak mudah diakses publik. Ini penting terutama ketika kasus melibatkan figur publik atau institusi besar. Privasi bukan hanya soal data, tapi juga soal keselamatan.
Ketika kepercayaan terbangun, korban lebih mungkin memberikan informasi tambahan dan memperbarui perkembangan kasus. Dengan begitu, relasi jurnalis dan korban tak bisa bersifat transaksional atau berakhir seketika berita tayang. Dalam proses yang berkelanjutan ini, jurnalis perlu membuka ruang untuk terus mendampingi serta menjaga komunikasi agar bisa memantau dampak liputan—termasuk kemungkinan trauma sekunder yang muncul pada korban, atau potensi eksploitasi oleh media lain. Maka, jurnalis wajib memberi penjelasan menyeluruh kepada korban dan pendamping tentang konsekuensi publikasi: potensi viral, reaksi publik, atau dampak psikososial lainnya. Penerapan perspektif interseksionalitas—yaitu perspektif yang melihat keterkaitan identitas sosial dalam membentuk pengalaman seseorang—menjadi urgen di sini.
Pasalnya, setiap korban memiliki latar sosial berbeda: kelas ekonomi, usia, gender, disabilitas, atau identitas lainnya. Kondisi ini membentuk kerentanan yang tidak bisa disamaratakan. Karena itu, narasi jurnalistik harus mempertimbangkan posisi korban dalam struktur sosial yang kompleks. Penggunaan formulir persetujuan (consent) dapat menjadi satu alat yang mendukung prinsip keadilan, transparansi, dan partisipasi korban dalam proses peliputan. Reaksi publik boleh jadi beragam. Namun, selama proses liputan dijalankan secara etis, jurnalis tetap berada di posisi yang bisa dipertanggungjawabkan. Semakin jurnalis memahami konteks ini, semakin kuat pula keberpihakan yang bisa ia bangun dalam tulisannya.
Adapun dalam proses penulisan, setiap kata mengandung makna. Penggunaan kata tak pernah bersifat netral maupun berdiri di ruang hampa. Narasi yang sensasional, tergesa, atau tanpa konteks dapat memperdalam luka korban. Pilihan diksi, struktur tulisan, dan cara menyebut korban perlu dipertimbangkan. Tak semua detail perlu dimuat. Tugas jurnalis bukan menelanjangi pengalaman, tetapi memaknai dan menyalurkan pesan keadilan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual—yang merupakan hasil perjuangan masyarakat sipil—dapat menjadi rujukan hukum yang penting, karena mengusung semangat keberpihakan pada korban, meski petunjuk teknisnya belum disosialisasikan. Untuk kasus di lingkungan kampus, jurnalis perlu memahami regulasi internal seperti aturan Kemendikbud Ristek dan kebijakan rektorat agar bisa menavigasi sistem birokrasi dan menjembatani korban dengan jalur keadilan. Di samping itu, menjalin jaringan dengan pakar, aktivis, dan pendamping korban akan memperkaya sudut pandang serta memperkuat kredibilitas liputan.
Baca juga: Pemberitaan kekerasan seksual
Bagaimana dengan publikasi? Untuk independensi, umumnya naskah jurnalistik tidak diberitahukan kepada informan sebelum ditayangkan guna menghindari intervensi. Melainkan, setelah naskah terbit, media mempersilakan para pihak untuk menggunakan hak jawab ketika terdapat informasi yang perlu diklarifikasi. Hak jawab adalah hak untuk menanggapi atau menyanggah pemberitaan yang dianggap merugikan nama baik. Namun, dalam kasus kekerasan seksual, jurnalis perlu mempertimbangkan kondisi korban yang berada dalam kondisi psikologis tidak berdaya, hingga mungkin tidak sanggup menggunakan hak jawab ketika pemberitaan tidak sesuai dengan situasinya. Alih-alih mendukung, ini justru berpotensi menimbulkan trauma baru pada korban. Sehingga, lebih baik jurnalis meminta tanggaoan maupun konfirmasi korban sebelum naskah diterbitkan.
Dengan demikian, menulis kasus kekerasan seksual senantiasa menuntut refleksi mendalam. Ini bukan hanya soal data yang cukup, tetapi juga soal bagaimana data tersebut dirangkai menjadi narasi yang adil. Ini juga bukan pekerjaan sederhana, tetapi dengan empati, kepekaan, dan keberpihakan pada korban, jurnalis bisa berperan sebagai bagian dari perjuangan menuju keadilan. Bukan hanya merekam luka, tapi juga menyuarakan harapan.
Baca juga: Seni mencegah kekerasan berbasis gender
Wiji Nurasih saat ini aktif bekerja di Divisi Penelitian dan Advokasi Mitra Wacana
Editor: Syaima Sabine Fasawwa